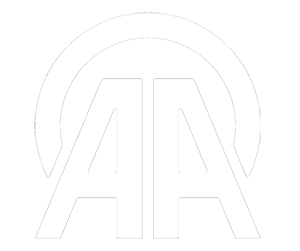OPINI - Sekilas tentang asal-usul genosida Myanmar
Genosida pertama yang diselenggarakan secara terpusat oleh diktator militer Jenderal Ne Win di Rangoon telah memasuki tahun ke-42 pada 12 Februari
 Ilustrasi: Warga Rohingya. (Foto file - Anadolu Agency)
Ilustrasi: Warga Rohingya. (Foto file - Anadolu Agency)
Greater London
Maung Zarni
Penulis adalah koordinator untuk Koalisi Pembebasan Rohingya Burma dan anggota Pusat Dokumentasi Genosida di Kamboja.
LONDON
Perintah sementara Mahkamah Internasional 23 Januari dalam kasus yang diajukan oleh Gambia terhadap Myanmar dirancang untuk melindungi Rohingya dan menjaga lokasi terjadinya kejahatan.
Keputusan itu telah membawa angin segar bagi jutaan warga Rohingya, baik yang berada di Myanmar, yang mengungsi di Bangladesh maupun yang berdiaspora di berbagai negara.
Ini merupakan tindakan paling signifikan yang diambil masyarakat internasional sejak Rohingya menjadi sasaran kebijakan nasional diskriminasi, pencabutan hak, pemindahan dan deportasi destruktif oleh berbagai organ negara di Myanmar.
Kasus yang dibawa Gambia ke pengadilan berfokus secara sempit pada peristiwa kekerasan tahun 2016 dan 2017.
Namun, sangat penting untuk melihat penganiayaan kelompok ini dalam konteks yang tepat, yang dimulai dengan dalih palsu dari upaya Myanmar untuk menindak migrasi ilegal melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh yang membentang sepanjang 270 mil.
Faktanya, genosida pertama yang diselenggarakan secara terpusat oleh diktator militer Jenderal Ne Win di Rangoon, yang melibatkan berbagai lembaga, tidak hanya pasukan pemerintah dan kepolisian tetapi juga departemen atau kementerian urusan agama, adat istiadat, dan berbagai cabang intelijen, telah memasuki tahun ke-42 pada 12 Februari.
Paradoksnya, ini juga merupakan tanggal di mana Myanmar merayakan “Hari Persatuan”, hari di mana mayoritas masyarakat Myanmar yang beragama Budha Birma dan beberapa minoritas nasional di sepanjang perbatasan kolonial Burma sepakat untuk menggabungkan wilayah mereka secara sukarela untuk membentuk satu negara merdeka yang memperoleh federasi tunggal pada 1947.
Pada hari yang sama, di Rakhine, sebuah negara bagian di Myanmar barat yang berbatasan dengan Bangladesh, Myanmar meluncurkan deportasi kekerasan yang pertama kali dilakukan terhadap ratusan ribu orang Rohingya.
Mayoritas dari mereka dilahirkan dan dibesarkan di wilayah tersebut dan memiliki kartu identitas resmi serta dokumentasi yang membuktikan kewarganegaraan Myanmar.
Pembersihan etnis dilakukan dalam dua fase di bawah operasi gaya militer yang secara kolektif dikenal sebagai “Operasi Dragon King”.
Fase pertama diluncurkan di ibu kota negara bagian Rakhine, Sittwe, pada 12 Februari 1978 dan hanya berlangsung selama seminggu, melibatkan 200 pasukan antarlembaga yang melakukan berbagai aksi kekerasan dan teror.
Fase kedua dilakukan di Kota Buthidaung dan Maungdaw di utara Rakhine dengan 400 pasukan keamanan antarlembaga.
Tentara Myanmar melakukan pembakaran, pembantaian, pemerkosaan dan metode teror lainnya di wilayah yang penduduknya damai, tidak bersenjata dan patuh sebagaimana dibuktikan dalam laporan surat kabar Bangladesh, Pakistan, dan kawasan Asia lainnya ketika itu.
Tindakan "teror" atau "kepanikan" itu menyebabkan eksodus Rohingya berskala besar pertama - sekitar 250.000 orang menurut catatan intelijen Myanmar – yang melintasi perbatasan ke Bangladesh yang, dengan intervensi militer langsung India, menang dari perang sipil dan merdeka dari Pakistan Barat pada 1971.
Dalam bukunya yang berbahasa Burma berjudul “Masalah di Gerbang Barat Myanmar” (2016), Khin Nyunt, seorang mantan jenderal, kepala dinas intelijen militer dan perdana menteri Myanmar, mencatat jumlah penduduk Muslim yang tidak dapat membuktikan kewarganegaraan atau tempat tinggal sah mereka (atau yang disebutnya pelanggar hukum imigrasi) berjumlah 643 (dari total penduduk 108.431) di Kota Buthidaung dan 458 (dari total penduduk 125.893) di Kota Maungdaw.
Jumlah yang sangat kecil dari mereka yang ditemukan tanpa dokumen identifikasi nasional Myanmar menunjukkan pencapaian drastis dalam upaya Myanmar untuk mengontrol perbatasannya yang rentan dengan Bangladesh, salah satu negara berpopulasi Muslim terbesar di dunia.
Pada 1959, militer Myanmar pernah melakukan kebijakan imigrasi serupa di wilayah yang sama diRakhine utara.
Menurut biografi Jenderal Tin Oo, mantan panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, yang berjudul “Perjalanan Myanmar Menuju Demokrasi dan Thura U Tin Oo” (diterbitkan di Yangon pada 2016), saat itu Letnan Kolonel Tin Oo, dalam kapasitasnya sebagai komandan regional Rakhine, menangkap dan mendeportasi 11.380 migran ilegal yang tinggal di wilayah Rohingya di Rakhine utara ke Pakistan Timur.
Tin Oo mengisahkan bahwa dia mengatur dua titik pengusiran di sepanjang perbatasan kedua negara di mana semua penduduk Pakistan Timur tanpa dokumen legal, yang berjumlah ratusan, diminta berjalan melintasi perbatasan menuju Teknaf di Distrik Chittagong.
Dia mengatakan para migran ilegal menyeret langkah mereka untuk menyebrangi perbatasan, sementara pasukan Myanmar mengacungkan senjata ke arah mereka agar mereka melintasi perbatasan seperti yang diperintahkan.
“Di bawah ancaman nyata kekerasan, gerombolan ini tiba-tiba berlari ke Pakistan Timur," tutur Tin Oo
Kedua veteran dari angkatan bersenjata Myanmar ini memiliki pengalaman langsung ketika ditugaskan untuk mengurus imigrasi ilegal dari seluruh Pakistan Timur (hingga 1971) dan Bangladesh (sejak 1971).
Jumlah migran ilegal dari seberang perbatasan barat Myanmar telah dipastikan merosot dari 11.380 pada 1959 menjadi 1.100 pada 1978.
Meskipun jumlah ini terdokumentasi dengan baik, sejak 1970-an, pemerintah Myanmar khususnya Kementerian Pertahanan dan media massa yang dikendalikan negara, terus menyulut mitos bahwa Myanmar berada di bawah ancaman yang sangat nyata dari gelombang besar “orang Bengali” yang tak terkendali dan mengambil wanita-wanita Buddha, merebut tanah-tanah Buddha dan menyerbu desa-desa Buddha.
Dalam buku-buku mereka masing-masing, yang secara linguistik tidak dapat diakses oleh jurnalis internasional dan pengamat Myanmar, tidak sekali pun jenderal Tin Oo atau Khin Nyunt - yang tahu benar wilayah tersebut - menggunakan kata-kata "ancaman teroris" "pemisahan diri oleh Muslim" atau "perebutan wilayah".
Menurut mereka, baik Rohingya maupun Bengali dari seberang perbatasan tidak menimbulkan ancaman bagi Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, baik secara demografis, budaya maupun ekonomi.
Terlepas dari wacana resmi dan populer Myanmar tentang ancaman Bengali di Gerbang Barat Myanmar, imigrasi ilegal Muslim yang tidak diinginkan dari Pakistan Timur atau Bangladesh telah lama berhenti menjadi masalah nyata di lapangan.
Masalah sebenarnya adalah upaya militer Myanmar untuk membuat negara bagian Rakhine, Myanmar barat, kembali sejalan dengan visi ideologis mereka, yang menurutnya wilayah tersebut pernah murni beragama Buddha.
Dalam pengantar buku “Masalah di Gerbang Barat Myanmar” yang disebutkan di atas, mantan jenderal Khin Nyunt menguraikan mitos sejarah yang telah lama menuntun kebijakan penganiayaan militer - dan penghancuran – Rohingya.
"Para penulis sejarah Rakhine secara mencolok mencirikan negara dan wilayah mereka sebagai wilayah yang benar-benar bersih-Muslim, tidak ada orang Bengali," tulis Khin Nyunt.
Selama delapan tahun sejak dua tindak kekerasan di Rakhine pada 2012, para pemimpin Myanmar termasuk Aung San Suu Kyi telah menawarkan narasi yang berkembang tentang krisis di Rakhine kepada dunia, termasuk kontra-pemberontakan, konflik komunal, kurangnya pembangunan ekonomi, Terorisme Muslim dan kekerasan berlebihan.
Narasi itu merupakan bentuk penjelasan dan justifikasi untuk pola kekerasan dan pelembagaan negara yang dilembagakan, atau kejahatan terhadap Rohingya.
Namun, asal usul penghancuran Rohingya yang berkelanjutan dan dilembagakan dengan kuat tertanam dalam identitas kelompok itu sebagai Muslim.
Meskipun negara ini berbatasan dengan tetangga raksasa seperti India dan China, dengan populasi masing-masing lebih dari 1 miliar, keduanya padat penduduk dan keduanya memiliki sejarah migrasi yang tumpang tindih selama seribu tahun, baik perbatasan Indo-Burma maupun perbatasan Sino-Burma tidak dibingkai dalam narasi militer Myanmar sebagai krisis atau ancaman.
Baik China maupun India tidak didominasi Muslim, sedangkan kedua negara - terutama China - adalah sumber imigrasi massal ilegal ke Myanmar.
Justru, pembingkaian Rohingya yang berbasis agama sebagai sebuah ancamanlah yang membuat kebijakan Myanmar memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai genosida.
*Pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Anadolu Agency