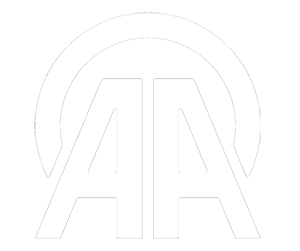Bunuh diri: Monster yang disimpan di dalam lemari
World Health Organization menyebut, satu orang di seluruh dunia mengakhiri nyawa sendiri setiap 40 detik. Di Indonesia, BPS mencatat 812 kasus bunuh diri pada 2015. Angka ini diperkirakan lebih besar karena tak semua kasus dilaporkan
 ilustrasi depresi. (Foto Anadolu Agency)
ilustrasi depresi. (Foto Anadolu Agency)
Jakarta Raya
Shenny Fierdha
JAKARTA
Tahun 2014 merupakan tahun terkelam bagi Sheila, 24 tahun, yang menolak menyebutkan nama sebenarnya untuk alasan privasi.
Di tahun itulah Sheila mencoba mengakhiri nyawanya lantaran tak kuat menahan depresi yang mengungkungnya. Saat sendirian di kamar mandi rumah kos yang terletak di Bandung, matanya terserobok pada sebotol detergen cair. Bak hilang akal, Sheila nekat menenggak detergen itu.
Mungkin tangan Tuhan masih menolongnya, mungkin pula bahan kimia dalam detergen itu tak cukup beracun untuk membunuhnya. Yang pasti, “Mulut saya jadi wangi sabun berhari-hari. Diare pun tidak!” dia berkelakar.
Momen itu terasa konyol kini, namun pada saat itu Sheila mengaku berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Dia merasa tak bisa menemukan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi.
Semua bermula pada 2011, ketika Sheila bertemu pria yang kemudian menjadi kekasihnya. Saat itu, lelaki tersebut memaksa Sheila untuk berhubungan intim di luar keinginannya. Dia diperkosa.
“Besoknya dia langsung meminta saya jadi pacarnya. Berhubung saya dibesarkan dengan adat Jawa yang kental, saya merasa bahwa karena dia sudah mengambil keperawanan saya, maka saya harus terus bersama dia, sehingga saya terima dia jadi pacar saya," tukas Sheila.
Mimpi buruknya tak berakhir. Selama tiga tahun berpacaran, pria itu berulang kali memperkosanya, bahkan membubuhi ancaman untuk menyebarkan foto-foto dan cerita tentang kegadisannya yang sudah terenggut kepada keluarga Sheila. Tahun-tahun itu, Sheila terperangkap neraka yang dia sendiri tak tahu jalan keluarnya.
Sheila mengaku mencoba bercerita kepada teman-temannya, mencari pertolongan. “Mereka malah menjauh,” kisah dia.
Merasa sendirian dan terjepit, tak ada jalan keluar lebih waras yang melintas di kepalanya kecuali membawa penderitaannya ke liang lahat.
Gagal menenggak detergen mendorongnya untuk lebih keras menggapai bantuan. Sheila, yang urung berkonsultasi dengan psikolog profesional karena menurutnya bakal mahal, memilih mengonsultasikan masalahnya pada seorang teman yang sedang menempuh studi S2 Psikologi.
Perlahan, Sheila belajar menuangkan kesedihannya dalam bentuk gambar, lukisan dan tulisan. Sang teman juga meyakinkan bahwa masih banyak yang masih mau menerima Sheila apa adanya, bila dia pun mau berdamai dengan dirinya sendiri.
Kini, keinginan bunuh dirinya hilang seiring waktu dan Sheila pun telah bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta Selatan. Kisah Sheila ini berakhir manis, karena tak jarang dalam kasus percobaan bunuh diri, banyak orang tak seberuntung Sheila.
World Health Organization (WHO) mengatakan, satu orang di seluruh dunia mengakhiri nyawa sendiri setiap 40 detik. Dalam setahun, ada sekitar 800.000 orang yang meninggal akibat bunuh diri.
Dalam laporan Global Burden of Disease (2004), WHO juga menyebut bunuh diri sebagai satu dari 20 penyebab utama kematian. Umumnya, pelaku bunuh diri dipicu oleh depresi.
Di Indonesia, riset terbaru tentang angka bunuh diri masih belum ada. Data WHO mengatakan terdapat 30.000 kasus bunuh diri di Indonesia pada 2005, 5.000 kasus pada 2010, 10.000 kasus pada 2012, dan 840 kasus pada 2013.
Sementara itu, berdasarkan data yang tercatat di kepolisian, Badan Pusat Statistik pada 2015 menemukan ada 812 kasus bunuh diri di Indonesia. Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah kasus bunuh diri tertinggi, yakni 331 kasus.
Angka ini diperkirakan lebih besar, karena tidak semua kasus percobaan bunuh diri dilaporkan ke polisi.
Depresi dan bunuh diri bukan prioritas
Ketiadaan data yang terbaru dan alpanya riset yang berhubungan dengan tingkat depresi dan bunuh diri di Indonesia seperti menunjukkan bahwa pemerintah tak menganggap depresi sebagai isu prioritas.
Ini diamini oleh Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) dr. Eka Viora, SpKJ.
"Kita masih berkutat pada penyakit yang sangat mendasar seperti gizi buruk, kematian ibu, kematian bayi, atau penyakit akibat infeksi," terang Eka.
Bak monster yang berbahaya karena kemampuannya membunuh umat manusia, dia tersimpan jauh di bagian belakang lemari yang tak terjangkau.
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza (P2MKJN) Kementerian Kesehatan, sebut Eva, sudah pernah membuat modul mengenai depresi dan bunuh diri serta cara pencegahan dan penanganannya. Mereka juga memberikan modul itu ke daerah-daerah disertai dengan pelatihan mengenai isu ini, namun menurut dia, tidak membuahkan hasil.
Direktur Direktorat P2MKJN Kementerian Kesehatan dr. Fidiansyah, SpKJ, MPH mengatakan, desentralisasi dan otonomi daerah memperlambat kebijakan dan program yang sudah dirumuskan di pusat untuk dijalankan di daerah.
Menurut ia, sejak 2011, perawat dan dokter di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sudah diberikan pelatihan dan pendidikan untuk menangani masalah kesehatan jiwa namun sampai 2012, dari sekitar 10.000 Puskesmas yang ada di Indonesia, baru 16 persen saja yang telah menjalankan program kesehatan jiwa.
“Kementerian Kesehatan tidak bisa memberikan teguran langsung kepada Puskesmas sebab itu kewenangan pemerintah daerah,” jelas Fidiansyah.
Baik Eka maupun Fidiansyah juga mengeluhkan pergantian orang di pemerintah pusat dan daerah yang berujung pada tidak berlanjutnya program yang sudah dijalankan sebelumnya.
Meski, Fidiansyah menolak jika pemerintah dikatakan tak memprioritaskan isu depresi dan bunuh diri. Menurut dia, Kementerian Kesehatan sudah mencantumkan isu kesehatan jiwa dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) yang dicapai melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019.
Namun kurangnya urgensi soal depresi dan bunuh diri bukan hanya berasal dari pemerintah saja, tapi oleh masyarakat juga.
Kementerian Kesehatan pada 2010 pernah mengadakan layanan hotline konsultasi pencegahan bunuh diri yang disebut ASA dan bisa diakses dengan menghubungi 500-454. Sayang, hotline ini hanya bertahan sampai 2014 karena tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, ada 161 orang penelepon yang menghubungi hotline itu sejak dibuka pada 2010, pada 2011 ada 222 penelepon, 2012 ada 347 penelepon, 2013 ada 267 penelepon, dan pada 2014 angka ini anjlok menjadi 46 penelepon saja.
Fidiansyah berujar, masyarakat yang menelepon hanya menanyakan informasi umum seperti di mana fasilitas kesehatan jiwa, alih-alih mengonsultasikan tentang bunuh diri.
“Mungkin karena belum membudayanya orang yang punya kecenderungan bunuh diri menelepon untuk minta bantuan,” tukas Fidiansyah.
Stigma “lemah dan kurang iman” yang kerap dilekatkan oleh masyarakat terhadap mereka yang mengalami depresi dan ingin bunuh diri, menurut dia, bisa jadi salah satu faktor yang membuat mereka urung meminta bantuan.
“Maka itu kita terus gaungkan bahwa kesehatan tidak hanya fisik tapi juga mental, spiritual, dan sosial. Itulah kesehatan manusia yang integral dan komprehensif,” tutup Fidiansyah.
Tak menyerah dengan ide hotline ASA, pada Juli 2016, Kementerian Kesehatan meluncurkan nomor telepon layanan gawat darurat 119 yang bisa dimanfaatkan untuk melaporkan kecelakaan, kondisi darurat medis, maupun dugaan bahwa orang yang kita kenal memiliki kecenderungan bunuh diri.
Ketidakberdayaan yang membunuh
Psikolog klinis dari yayasan peduli kesehatan psikologis di Jakarta Selatan Yayasan Pulih, Ahastari Nataliza, mengatakan depresi adalah pengalaman yang sangat subjektif.
Dia menggambarkannya sebagai keadaan psikologis ketika suasana hati seseorang sangat down akibat peristiwa dalam hidupnya. Pukulan ini begitu sulit diterima sampai orang tersebut merasa tidak berdaya.
"Skema besar pada orang depresif itu adalah ketidakberdayaan. Pemaknaan terhadap peristiwa atau cobaan dalam hidup pun berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, tergantung kepribadian masing-masing," terang psikolog yang akrab disapa Liza itu.
Dia mencontohkan, si A dan si B sama-sama kehilangan anggota keluarganya akibat bencana alam. Si A merasa sangat terpukul dan terpuruk, sementara si B walaupun sedih cepat bangkit dan bisa memaknai hikmah di balik cobaan itu.
"Makanya depresi itu subjektif sebab peristiwa penyebab depresi itu sendiri dimaknai secara subjektif oleh orang yang mengalaminya," tukas Liza.
Ciri umum orang depresif antara lain susah tidur atau kebanyakan tidur, nafsu makan menurun drastis atau bisa melonjak, mudah tersinggung, suka menyendiri, dan suasana hati yang down.
Berapa lama sampai depresi berkembang menjadi pemikiran bunuh diri, menurut Liza, tidak bisa dipukul rata mengingat sifat depresi yang subjektif.
"Namun umumnya ketidakberdayaan itu berkembang menjadi pemikiran bunuh diri saat si individu merasa dia tidak berguna," ungkap Liza.
Meski ciri orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri tidak jauh berbeda dari orang depresif, namun sebut Liza, yang paling menonjol dari mereka yang merencanakan bunuh diri adalah orang tersebut perlahan merencanakan tempat dan tanggal kapan dia akan mengambil nyawanya sendiri – terkadang juga termasuk metodenya.
Tak jarang, kata Liza, mereka akan menyebutkan hal-hal yang berbau kematian.
Saat orang yang kita kenal mengalami depresi dan seolah memiliki kecenderungan bunuh diri, saran Liza, yakinkan bahwa kita ada untuk mendengarkan ceritanya. Yakinkan juga bahwa masih banyak yang menyayangi dan membutuhkan dia sehingga akan banyak yang merasa kehilangan jika dia tiada.
"Tapi jangan banyak tanya karena akan membuat orang itu jadi risih dan defensif. Jangan paksa dia bercerita," tegas Liza.
Kita juga harus pertajam sensitivitas terhadap orang tersebut dan perbanyak observasi terhadap kelakuannya agar jika suatu ketika dia menampilkan perubahan perilaku drastis yang tampak seolah ingin mengakhiri hidup, kita bisa segera bertindak.
Ketika dia sudah bisa diajak berkomunikasi, coba sarankan dia untuk menemui psikolog atau tokoh agama untuk berkonsultasi.
"Salah satu bentuk terapi yang diberikan psikolog ialah solution-focused therapy yakni psikolog membantu individu fokus pada mengerucutkan langkah yang ingin dicapai sebagai solusi masalahnya," beber Liza.
Tidak ada ukuran pasti berapa kali sesi terapi harus dilakukan, sebab tergantung pada kompleksitas masalah dan ketersediaan waktu klien untuk mengikuti terapi.
Apabila individu yang mengalami depresi dan kecenderungan bunuh diri adalah kita sendiri, Liza menekankan pentingnya kita menyadari terlebih dahulu penyebab munculnya depresi dan kecenderungan bunuh diri tersebut selain juga tetap mencari bantuan profesional.
"Setelah disadari, kita harus terima bahwa hal itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kalau kita terus menolak, itu sama saja dengan not living in the moment dan itu tidak ada gunanya," tutup Liza.
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.