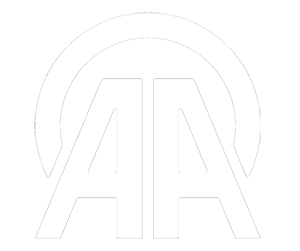WNI eks ISIS/Daesh berharap pulang di tengah pro kontra ancaman terorisme
Firda sekarang menjalani hari-harinya dengan penyesalan karena sempat bergabung dengan Daesh/ISIS, dan berharap diberikan kesempatan kembali ke Indonesia
 Ilustrasi: Seorang ibu membawa bayinya di kamp pengungsian Harbanush, Suriah. (Erdal Türkoğlu - Anadolu Agency)
Ilustrasi: Seorang ibu membawa bayinya di kamp pengungsian Harbanush, Suriah. (Erdal Türkoğlu - Anadolu Agency)
Jakarta Raya
JAKARTA
Berawal dari patah hati, Firda -bukan nama sebenarnya- meninggalkan seluruh hidupnya di Indonesia untuk bergabung dengan Daesh, atau yang dikenal dengan nama ISIS, di Suriah.
Firda, 25, dulu hidup di keluarga religius, namun dia menyebut dirinya yang sebagai “anak badung”.
Patah hati di usia 19 tahun memicu Firda berniat memperbaiki diri dan menebus masa lalunya dengan memperdalam agama.
Dia mencari saluran pembelajaran lewat internet, lalu menemukan ruang konsultasi yang ternyata dibuat oleh kelompok Daesh.
“Isinya bukan video sadis seperti yang di media, tetapi konsultasi tanya jawab dan aku betah di forum itu. Mereka bicara tentang hijrah yang bisa membuat seperti lahir kembali,” kata Firda kepada Anadolu Agency pada Minggu.
Dari situ dia mempelajari lebih jauh terkait paham Daesh hingga memutuskan untuk bergabung ke Suriah demi menegakkan “keadilan atas nama Islam”.
Firda meninggalkan Indonesia dan berangkat ke Istanbul, Turki pada Desember 2015.
Keluarganya mengira Firda pergi ke Turki untuk berwisata sekaligus melakukan riset untuk keperluan skripsi, padahal saat itu Firda berencana untuk tidak kembali.
Di Turki, Firda bertemu dengan seorang pria asal Algeria lalu menikah dan bersama-sama menyeberang ke Suriah. Mereka tiba di wilayah itu pada Juli 2016.
Firda mengandung anak pertamanya ketika menyeberangi Suriah. Anak laki-laki itu lahir di teritori kekuasaan Daesh, tepatnya di Al Bukamal pada Februari 2017.
Keluarga kecil Firda pernah tinggal di Al Bukamal dan Baghouz selama menjadi bagian dari Daesh.
Firda mengaku sebagai non-kombatan, lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak.
Namun, Firda mengatakan apa yang dia lihat di bawah pemerintahan Daesh berbeda dengan ekspektasinya. Komunikasi mereka dibatasi, perbudakan terjadi, dan perempuan menjadi korban ketidakadilan.
“Tetapi kita enggak boleh meninggalkan ISIS. Komunikasi kami dipantau. Pemerintahan versi mereka semaunya, rakyat enggak ada yang bisa bersuara,” ujar dia.
Pada Desember 2017, perempuan dan anak-anak Daesh termasuk Firda dipindahkan ke kamp al Roj, sementara para laki-laki tetap bertahan di wilayah kekuasaan Daesh.
Saat itu lah Firda terpisah dengan suaminya, hingga dia mendapat kabar bahwa suaminya telah meninggal pada Mei 2018.
Firda dan anaknya yang berusia tiga tahun menetap di salah satu tenda di kamp Al-Roj hingga saat ini.
Dia menjalani hari-hari dengan penyesalan, serta berharap bisa segera pulang ke Tanah Air.
“Aku ya kecewa, kesal, tapi mau disesali juga enggak mengubah apa-apa,” tutur Firda.
“Aku enggak akan balik badan lagi ke ISIS. Aku enggak mau mereka merekrut anggota baru,” lanjut dia.
Dia juga mengaku siap menjalani konsekuensi yang ditetapkan oleh pemerintah jika diberi kesempatan kedua untuk kembali ke Indonesia.
“Aku ingin diterima kembali, ada usaha untuk memperoleh kepercayaan orang,” ujar dia.
Menunggu keputusan pemerintah
Firda merupakan satu dari sekitar 600 warga negara Indonesia eks-Daesh yang berada di Suriah. Pemerintah Indonesia sejauh ini belum memutuskan bagaimana menyikapi nasib ke-600 orang tersebut.
Di dalam negeri, isu ini memicu perdebatan karena para returnees dikhawatirkan menimbulkan ancaman keamanan hingga “menebarkan paham terorisme”. Sebagian lainnya berdebat mereka layak dipulangkan dengan alasan kemanusiaan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan BNPT masih merumuskan masukan dari berbagai kementerian sebelum membuat keputusan yang memiliki resiko masing-masing.
“Enggak gampang, di dalam negeri saja bagaimana menjaga supaya bisa kondusif apalagi dengan menghadapi yang seperti ini,” kata Suhardi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan informasi yang diterima BNPT, para WNI itu tersebar di tiga kamp pengungsian Al Hol, Al Roj dan Ainisa di Suriah. Sebagian besar merupakan perempuan dan anak-nak.
Menurut Suhardi, jumlah dan data pasti dari para WNI belum terverifikasi karena mereka tidak memiliki paspor lagi.
“Informasi ini masih mentah sehingga perlu diverifikasi,” tutur dia.
Indonesia sebetulnya memiliki pengalaman memulangkan WNI eks-kombatan Daesh. Pada 2017, pemerintah memulangkan 18 WNI yang bergabung dengan kelompok teroris tersebut di Suriah.
Sebagian masih menjalani proses pidana di Indonesia karena melanggar Undang-Undang Terorisme, sedangkan perempuan dan anak-anak menjalani rehabilitasi dan program deradikalisasi.
Menurut Suhardi, proses rehabilitasi dan deradikalisasi eks-kombatan Daesh tidak mudah, membutuhkan waktu panjang, serta memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.
“Termasuk seorang anak yang baru tahap pelatihan, belum menjadi fighter. Itu jadi binaan BNPT, butuh waktu tiga tahun untuk adaptasi. Bayangkan susahnya menghilangkan traumanya,” jelas Suhardi.
Ancaman keamanan dalam negeri
Pengamat terorisme dari Yayasan Prasasti Perdamaian, Taufik Andrie meminta pemerintah mewaspadai resiko keamanan jika WNI eks Daesh dipulangkan.
Kepulangan mereka, lanjut dia, berpotensi membawa dinamika baru terhadap pergerakan jaringan teror di Indonesia.
Pemerintah perlu memastikan para WNI ini tidak terhubung atau dihubungi dengan jaringan di dalam negeri untuk mencegah ancaman teror.
“Mereka pulang itu seolah ‘pahlawan perang’ bagi pendukung ISIS sehingga glorifikasinya dikhawatirkan membuat yang lain terinspirasi,” kata Taufik kepada Anadolu Agency.
Sejauh ini Taufik menilai pemerintah belum cukup siap untuk menangani WNI eks Daesh secara komprehensif.
“Presedennya sudah ada, sepanjang 2016-2018 itu ada kelompok deportan, beberapa returnees yang kembali ke Indonesia. Tidak ada penanganan komprehensif dari pemerintah,” ujar dia.
“Mereka terhubung dan dihubungi oleh jaringan lokal dan menjadi bagian dari kelompok yang merencanakan serangan teror di 2018 hingga 2019, ini menunjukkan bahwa ini tidak cukup efektif,” lanjut Taufik.
Salah satu contohnya adalah pasangan suami istri pelaku bom bunuh diri di gereja Sulu, Filipina bernama Rullie Rian Zeke dan Ulfah Handayani Saleh pada 2019.
Rullie dan Ulfah dideportasi dari Turki setelah terdeteksi hendak berangkat ke Suriah pada 2017. Mereka mengikuti program deradikalisasi selama satu bulan, lalu dipulangkan ke daerah asal.
Pada 2019 keduanya dinyatakan sebagai pelaku bom bunuh diri di gereja Filipina.
Menurut dia, pemerintah perlu mengklasifikasikan para WNI eks Daesh berdasarkan tingkat keterlibatan dan keterpaparannya untuk menentukan langkah penanganan berikutnya, apakah dipidana atau direhabilitasi.
“Siapa saja yang masuk kawasan perang sebagai kombatan akan lebih mudah diajukan ke persidangan, tetapi konsruksi hukumnya lemah sehingga persidangannya akan rumit,” kata dia.
Sedangkan proses rehabilitas dan deradikalisasi, lanjut Taufik, perlu mencakup aspek ideologi, psikologi, reedukasi, penghidupan serta integrasi sosial untuk kembali ke masyarakat.
Namun suka tidak suka, dia mengatakan pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada para WNI itu.
“Hukum internasional tidak mengenal orang terlunta-lunta di negeri asing. Otoritas setempat pasti menghubungi pemerintah Indonesia dan wajib direspons,” kata dia.
Hukum humaniter internasional
Menurut Palang Merah Internasional (ICRC), dua per tiga dari 70 ribu orang yang menempati kamp Al-Hol di Suriah merupakan perempuan dan anak-anak.
Media officer ICRC, Mari Aftret Mortvedt menuliskan bahwa kehidupan anak-anak di kamp itu tidak mudah.
“Anak-anak berusia empat atau lima tahun ditugaskan untuk membawa air. Mereka melakukannya sebagai tim, tetapi membawa air bervolume berat pada jarak yang jauh adalah tugas yang sulit bagi anak-anak,” tulis Mari dikutip dari situs resmi ICRC.
ICRC, tulis dia, tidak dalam kapasitas untuk memulangkan mereka namun tetap memperingatkan pemerintah berbagai negara terkait tanggung jawab terhadap warga negara mereka.
Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sigit Riyanto mengatakan dalam konteks individu mereka berhak mendapatkan perlindungan termasuk dari negaranya,
Sigit menuturkan anak-anak dan perempuan non-kombatan juga harus diprioritaskan jika dilihat dari sudut pandang hukum humaniter internasional.
“Kalau anak-anak negara wajib turun tangan beri perlindungan,” kata Sigit kepada Anadolu Agency.
Namun jika ada WNI dewasa yang menolak perlindungan itu, maka negara tidak wajib untuk memulangkannya.
“Bisa jadi yang bersangkutan melepaskan kesetiannya pada negara asalnya, tidak ingin lagi setia pada negaranya dia tidak lagi menginginkan perlindungan pada negara asalnya. Indonesia tidak punya kewajiban memulangkan mereka,” jelas dia.
Pengamat terorisme Taufik Andrie mengatakan upaya perlindungan terhadap anak-anak cukup kompleks.
Beberapa dari mereka menunjukkan pernah terlibat dalam pelatihan para militer atau operasi kekerasan.
“Kita kan tidak tahu, apakah perempuan dan anak-anak tidak semua innocent, jadi harus di-addressed betul konsep ideologinya, psikologisnya, post-traumatic disorder syndrom, kemudian program deradikalisasi atau rehabilitasi yang tepat,” kata Taufik.
“Anak-anak seperti ini pendekatannya memang tidak mutlak harus didekati sebagai pelanggar hukum pidana tapi tidak bisa juga diselesaikan sebagai anak-anak biasa. Masa depan mereka masih panjang,” lanjut dia.