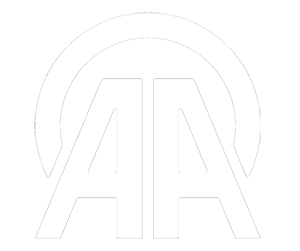REPORTASE: Mengurai tantangan 14 tahun perdamaian Aceh
Pembangunan ekonomi Aceh masih berjalan di tempat, tantangan yang dihadapi dinilai ada pada warga Aceh sendiri
 Zaini Abdullah (79) saat wawancara dengan Anadolu Agency (Foto file - Anadolu Agency)
Zaini Abdullah (79) saat wawancara dengan Anadolu Agency (Foto file - Anadolu Agency)
Jakarta Raya
BANDA ACEH
Selamat Hari Damai Aceh ke-14. Perdamaian Menuju Aceh Hebat dan Sejahtera.
Kalimat itu terpampang dalam sebuah baliho di jalan-jalan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Baliho tersebut dipasang Pemerintah Aceh menyambut empat belas tahun penandatanganan Memorandum of Understanding Helsinki di Finlandia atau dikenal sebagai MoU Helsinki.
MoU ini menjadi sejarah bagi masyarakat Aceh karena dengan MoU itu perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dapat dicapai.
Pada 15 Agustus 2005, kedua pihak sepakat berdamai setelah terlibat konflik selama hampir 30 tahun.
Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, sedangkan GAM mengutus Malik Mahmud Al Haytar untuk menandatangani MoU Helsinki.
Zaini Abdullah, 79, salah seorang tokoh masyarakat Aceh yang terlibat dalam proses perdamaian, masih tidak lupa saat detik-detik perumusan perdamaian dilaksanakan.
Menurut dia, perjanjian damai itu sedianya berlangsung di Jenewa dan Tokyo pada 2003. Namun usaha-usaha tersebut selalu gagal.
Perdamaian GAM dan Pemerintah RI, kata dia, benar-benar terwujud saat di Helsinki atas usaha Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada 2005.
Jusuf Kalla meminta Presiden Finlandia saat itu Marti Ahtisari sebagai penengah perdamaian.
“Marti Ahtisari sudah banyak menginisiasi perdamaian di internasional,” ujar Zaini Abdullah, yang juga mantan Menteri Luar Negeri GAM ini kepada Anadolu Agency di kediamannya di Banda Aceh, pada Selasa pagi.
Proses perdamaian pada saat itu, kata dia, berlangsung cepat dibanding masa-masa sebelumnya.
Sebab perundingan pada saat itu bermula pada Januari 2005, tapi sudah berhasil meneken MoU damai pada Agustus 2005.
“Jadi hanya delapan bulan. Kami sama-sama ingin damai,” kata Zaini yang aktif sebagai dokter di sejumlah Rumah Sakit di Swedia pada kurun waktu 1982–2005.
Salah satu faktor yang membuat perjanjian damai cepat tercapai karena terjadi bencana nasional tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004.
Setelah bencana tsunami itu, cerita Zaini, pihak Indonesia dan Aceh tergerak untuk bertemu dan secara serius mewujudkan perjanjian damai.
Zaini mengaku bersyukur perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah RI telah terwujud.
Kesepakatan damai ini, terang dia, membuat tidak ada lagi perang antara GAM dan Pemerintah Indonesia. Masyarakat Aceh juga bisa hidup dengan damai.
Sisa persoalan
Namun demikian, Zaini tetap meminta komitmen pemerintah pusat untuk menjalankan butir-butir yang belum terlaksana, seperti lambang, bendera, dan hymne.
Zaini mengatakan bendera Aceh tidak harus persis sama dengan bendera GAM.
“Itu hanya perlu ada perubahan sedikit dari bendera GAM sebelumnya,” kata dia.
Selain itu, Zaini menyarankan pemerintah pusat harus lebih banyak berdialog dengan masyarakat Aceh.
Dia juga meminta pemerintah Aceh saat ini menjalankan moratorium izin usaha tambang sebagaimana dulu dia lakukan saat menjabat Gubernur Aceh pada 2012-2017.
Kebijakan itu digulirkan Zaini untuk menyelamatkan hutan dan lahan Aceh dari tangan-tangan orang tak bertanggung jawab.
Selama menjabat menjadi Gubernur, Zaini berhasil menekan 138 Izin Usaha Perusahaan (IUP) seluas 841 ribu hektare menjadi 37 IUP dengan luasan 156 ribu hektare.
“Kita harus memberikan waktu bagi SDM Aceh untuk dapat mengelola tambangnya sendiri,” kata dia.
Jika pada saat ini usulan referendum kembali mengemuka, Zaini termasuk mantan petinggi GAM yang tidak setuju dengan ide itu.
Menurut Zaini, hal tersebut akan membawa Aceh kembali pada konflik.
“Referendum sama saja kita kembali ke nol,” kata dia.
Namun demikian, Zaini melihat ada kekecewaan dari masyarakat Aceh karena perjanjian Helsinki belum maksimal dijalankan.
“Pemerintah Indonesia harus menangkap ini sebagai pesan,” kata dia.
Juni lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah membentuk tim kajian dan advokasi terhadap Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan butir-butir perdamaian antara Indonesia dengan GAM.
Tujuan DPRA membentuk tim ini karena isi perjanjian damai belum sepenuhnya dijalankan.
Tim yang diberi nama Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki 2005 dan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 akan fokus pada aspek kewenangan dan pendapatan Aceh.
Anggota Komisi I DPRA Azhari Cage menjelaskan tujuan pembentukan tim tersebut untuk membentuk mencari titik temu permasalahan hasil MoU Helsinki dan UU PA.
Menurut dia, perjanjian damai yang baru berjalan hanya tiga, yaitu Otonomi khusus (Otsus), Partai Lokal, dan Lembaga Wali Nanggroe.
Sementara poin lainnya seperti bendera, lambang, pembagian hasil migas, batas wilayah Aceh hingga kini belum terealisasi.
Tantangan internal
Pakar hukum sekaligus pemerhati politik dari Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam mengatakan butir-butir perjanjian Helsinki yang belum dijalankan bukanlah faktor utama yang membuat pembangunan Aceh masih terhambat.
Saifuddin mengatakan tantangan Aceh ada pada urusan internalnya sendiri. Hal ini membuat pembangunan ekonomi berjalan di tempat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Aceh masih bertahan sebagai provinsi nomor satu termiskin di Sumatera. Jumlah penduduk miskin di Tanah Rencong saat ini berjumlah 831 ribu orang atau 15,68 persen.
Saifuddin menampik alasan tidak optimalnya kewenangan pemerintah Aceh dalam mewujudkan pembangunan.
Pasalnya, kata Saifuddin, Otonomi Khusus yang berlaku di Aceh dapat dioptimalkan untuk menekan angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.
Berdasarkan data DPRA Aceh, sejak tahun 2008 hingga 2019, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh sebesar Rp73,83 Triliun.
Sedangkan khusus pada 2019, pemerintah pusat mengalokasikan dana otsus sebesar Rp8,37 triliun untuk Provinsi Aceh.
“Jadi walau dana Otsus sudah banyak digulirkan, tapi Aceh masih menyisakan persoalan,” terang dia kepada Anadolu Agency.
Menurut Saifuddin, kondisi ini terjadi karena masyarakat Aceh terlalu disibukkan dengan kegiatan politik sehingga tidak fokus melakukan pembangunan.
Saifuddin mencatat setidaknya ada enam penyelenggaraan pemilu sejak perjanjian damai diteken yang telah menguras energi eksekutif, legislatif, dan masyarakat Aceh.
Pemilu itu antara lain Pilkada 2006, Pemilu legislatif dan eksekutif 2009, Pilkada 2012, Pemilu legislatif dan eksekutif 2014, Pilkada 2017, dan Pemilu legislatif dan eksekutif pada 2019.
“Jarak satu pemilu ke pemilu lainnya sangat berdekatan sehingga masyarakat Aceh tidak sempat membangun,” kata penulis buku Survey Penanganan Konflik Aceh (2015) ini.
Kondisi ini membuat rancangan-rancangan pembangunan yang telah dirumuskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) tak bisa berjalan maksimal di lapangan, baik di tingkat pemerintah, kabupaten, dan kota di wilayah Aceh.
Menurut Saifuddin, kontestasi politik yang banyak menyedot energi masyarakat Aceh membuat badan legislatif di Aceh tidak optimal melakukan fungsi pengawasan dan budgeting.
Hal ini, lanjut dia, berdampak pada rendahnya kuantitas peraturan daerah atau qanun yang dikeluarkan.
Dia menyatakan Aceh butuh waktu untuk bangkit karena menyelesaikan persoalan di wilayah bekas perang tidak seperti membalik telapak tangan.
Dia menerangkan pilkada serentak, yang memberikan jeda lima tahun ke pemilu berikutnya, adalah salah satu jalan bagi Aceh untuk menuntaskan rancangan-rancangan strategis pembangunan.
Pekerjaan rumah partai lokal
Saifuddin juga mendorong partai-partai lokal Aceh untuk dapat membangun kepercayaan publik di Aceh.
Dia menyoroti suara Partai Aceh yang terus melorot dalam setiap pemilu legislatif, padahal Partai Aceh adalah partai lokal bentukan mantan kombatan GAM.
Berdasarkan data Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dalam Pileg pertama pada 2009, Partai Aceh berhasil menguasai DPRA dengan perolehan 33 kursi dari 69 kursi.
Sementara pada Pileg 2014, Partai Aceh kehilangan empat kursi di tengah bertambahnya jumlah kursi di parlemen.
Partai Aceh saat itu hanya mengantongi 29 dari total 81 kursi.
Sedangkan pada Pileg 2019, Partai Aceh hanya memperoleh 18 dari total 81 kursi yang diperebutkan.
Meski Partai Aceh masih menempati posisi nomor 1 pada Pileg 2019, perolehan suara partai-partai nasional terus membuntuti dan dapat mengungguli partai-partai lokal Aceh lainnya.
Antara lain Demokrat (10 kursi), disusul Golkar (9 kursi), Gerindra (8 kursi), Partai Nasional Aceh (6 kursi), PAN (6 kursi), PKS (6 kursi), PPP (6 kursi), PKB (3 kursi), Partai Damai Aceh (3 kursi), NasDem (2 kursi), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (1 kursi), Hanura (1 kursi), PDIP (1 kursi), PKPI (1 kursi).
Saifuddin menilai kondisi ini tak lepas dari koreksi warga Aceh terhadap kiprah partai lokal.
“Salah satu penyebabnya adalah perpecahan internal yang dihadapi partai,” jelas pria yang melalukan penelitian mengenai partai lokal Aceh pada 2009 ini.
Sebaliknya, kata dia, warga Aceh masih menilai partai-partai nasional walaupun terkesan sentralistik, namun masih diisi dan dapat menyerap aspirasi warga Aceh.
Saifuddin menyarankan agar-agar partai lokal Aceh melakukan kaderisasi dan tidak bertumpu pada satu-dua figur.
“Rekrutmen dan pola komunikasi kepada konstituen harus berlangsung secara strategis dan terencana,” tutur dia.
Partai Aceh, menurut Saifuddin, sudah mencium persoalan ini. Mereka mulai melakukan rekrutmen terbuka di media dan menyasar kelompok muda.
“Ini tawaran bagus dari Partai Aceh untuk kontestasi politik,” jelas dia.
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.