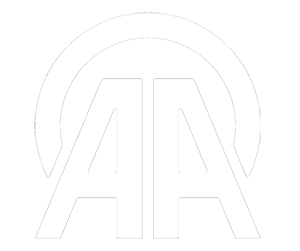OPINI - Facebook vs Pemerintah Australia: Antara hak publik dan hegemoni platform
Pada Selasa, 23 Februari 2021, setelah negosiasi berhari-hari, Facebook menghentikan pemblokiran. Namun, bagaimanapun juga, kejadian ini menunjukkan sebuah relasi yang timpang antara platform dan penerbit
 Ilustrasi: Facebook. (Foto file - Anadolu Agency)
Ilustrasi: Facebook. (Foto file - Anadolu Agency)
Jakarta Raya
Penulis adalah Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2014-2017. Saat ini sedang menempuh Master in Public Administration di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
SINGAPURA
Facebook memblokir akses ke laman berita di Australia. Pemblokiran ini buntut dari upaya pemerintah Australia menuntut Facebook dan Google memberi kompensasi kepada laman berita yang kontennya diakses melalui dua platform ini. Google menyanggupi. Facebook memilih jalan lain; memblokir akses ke laman berita di Australia.
Pro dan kontra pun muncul. Satu pihak menilai Facebook unjuk kuasa dan merundung pemerintah Australia. Pihak lain menyalahkan pemerintah Australia karena membuat Facebook melakukan langkah drastis seperti ini sehingga membuat hak warga Australia atas informasi terbatasi.
Parlemen Australia menyebut Rancangan Undang-undang Daya Tawar Media ini diadakan dalam rangka meningkatkan daya tawar bisnis berita dengan platform digital. Dalam risalah pembahasan RUU ini di parlemen Australia disebut media “menderita penurunan yang cukup besar dalam penghasilan dari display dan iklan baris.”
William Easton, Direktur Pelaksana Facebook Australia dan Selandia Baru, menyatakan, RUU ini salah memahami hubungan antara platform dengan penerbit.
“Membuat kami menghadapi pilihan pahit; mencoba patuh pada hukum yang mengabaikan realitas hubungan ini, atau berhenti membolehkan konten berita di layanan kami di Australia. Dengan berat hati, kami memilih yang terakhir,” kata Easton dalam siaran resmi di laman blog Facebook.
Selasa, 23 Februari 2021, setelah negosiasi berhari-hari, Facebook menghentikan pemblokiran. Pemerintah Australia melunakkan beberapa posisinya antara lain memberikan kesempatan mediasi dalam proses tawar-menawar antara Facebook dengan penerbit.
Namun, bagaimanapun juga, kejadian ini menunjukkan sebuah relasi yang timpang antara platform dan penerbit.
Relasi Platform-Penerbit
Satu premis yang sering dikumandangkan pendukung langkah pemerintah Australia adalah, terjadi “perpindahan” iklan dari media jurnalistik (penerbit) ke platform. Premis ini kemudian menjadi alasan bahwa platform harus membayar kompensasi karena meraup keuntungan dari konten yang dibuat penerbit.
Premis ini di satu sisi ada benarnya. Sejak kemunculan platform-platform seperti Yahoo!, Google, Facebook, YouTube, pemasang iklan meninggalkan platform iklan lama seperti media cetak, radio, dan televisi. Namun jika memakai pendekatan konsumen dalam melihat belanja iklan ini, sesungguhnya pergeseran pemasang iklan adalah mengikuti konsumen. Di mana konsumen banyak berkumpul, di sanalah pemasang iklan pergi.
Bukan berarti konsumen media lama seperti media cetak, radio, dan televisi yang bergeser. Analisis paling pas adalah, konsumen media lama tidak tumbuh, sementara konsumen baru mengonsumsi media digital terus membesar.
Memang ada konsumen lama yang migrasi, disebut digital migrant, yakni generasi kelahiran sebelum 1990-an yang sebelumnya konsumsi media lama, lalu belakangan menggunakan Internet. Namun memasuki dekade kedua abad 21, demografi terbesar adalah yang dari awal terbiasa dengan Internet (digital native).
Media sosial seperti Facebook, diungkapkan mantan design ethicist Google Tristan Harris dalam film “The Social Dillema”, melakukan tiga hal; keterikatan (engagement), pertumbuhan (growth), dan iklan.
Rumus tiga serangkai ini mungkin dimiliki penerbit, namun dengan teknologi yang terbatas. Sementara media sosial mengembangkan teknologi yang sophisticated sehingga mencapai apa yang disebut Shoshana Zuboff (2019) sebagai “surveillance capitalism” yakni penggunaan data perilaku pengguna sebagai komoditas.
Media sosial membuat pengguna sedemikian rupa terikat dengan platform lewat beragam teknik persuasi berbasis algoritma dan machine learning. Perilaku pengguna tercatat dan dianalisis menghasilkan pola tertentu yang akan direspons oleh mesin secara personalized. Jika pengguna menyukai konten-konten kuliner, maka mesin akan merekomendasikan konten-konten kuliner muncul di linimasa pengguna.
Kemudian setiap pengguna juga diarahkan mengajak orang lain untuk turut menggunakan media sosial yang dia pakai (growth). Ketika Elon Musk mempromosikan sebuah media sosial baru, maka beramai-ramai orang ikut mencoba media sosial yang dia promosikan.
Kombinasi keterikatan dan pertumbuhan ini yang membuat media sosial menjadi sebuah mesin periklanan yang efektif. Iklan bisa lebih efektif menyasar pengguna, berdasarkan usia, konten yang disukai, preferensi politik, tempat tinggal, dan sebagainya. Teknologi inilah yang penerbit tidak pernah miliki karena memang bukan didesain sebagai media sosial.
Malah yang terjadi adalah penerbit kemudian menumpang ke media sosial untuk memanfaatkan kerumunan pengguna. Bahkan ada penerbit yang juga membeli iklan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Bukan hanya pengguna biasa yang ketergantungan pada media sosial tapi juga penerbit.
Setiap Orang Media
Internet telah mengubah perilaku orang mengonsumsi informasi. Tahun 1990-an akhir, Yahoo! News mengenalkan format directory kepada pengguna untuk memilih sendiri berita yang ingin dibaca, setelah ratusan tahun konsumen harus menerima editor media yang memilihkan untuk mereka.
Lalu muncul Google mengenalkan teknologi pencarian yang membuat konsumen bisa mencari informasi yang dibutuhkan saja. Di akhir tahun 2000-an, media sosial mengenalkan teknologi share yang membuat orang mengonsumsi informasi yang dibagikan orang lain di laman media sosial mereka. Dan belakangan, aplikasi pesan seperti WhatsApp membuat share yang lebih baik lagi: rekomendasi.
Kemampuan media sosial buat mengikat, tumbuh, dan beriklan membuat setiap penggunanya menjadi media itu sendiri. Penerbit bersaing dengan perorangan yang mampu menghasilkan konten. Perorangan menjelma menjadi media yang besar, mampu merekrut puluhan bahkan ratusan tenaga kerja untuk memproduksi konten. Penghasilan para content creator di YouTube dan Facebook ini bahkan bisa melebihi penghasilan penerbit.
Bagaimana nasib penerbit dalam situasi yang didominasi media sosial ini? Salah satu respons adalah homeless media yaitu media yang hanya eksis di media sosial. Media ini memanfaatkan media sosial untuk distribusi. Iklannya bisa langsung di dalam konten atau memanfaatkan alat dari media sosial tersebut.
Pendekatan yang win-win tentu adalah bagi hasil iklan. Google memiliki format bagi hasil. Bahkan dalam “pertarungan di Australia”, Google bersedia duduk bersama penerbit membicarakan format bagi hasil yang lebih baik untuk penerbit.
Facebook sebenarnya memiliki format kerja sama bagi hasil dengan penerbit yang disebut sebagai Instant Article. Penerbit yang bekerja sama dengan Facebook bisa memasang kontennya dengan mengenakan kode tertentu agar tayang sebagai Instant Article di Facebook. Konten ini bisa dipasang iklan sendiri oleh penerbit atau menggunakan iklan melalui Facebook. Penghasilan dari iklan ini dibagi.
Problemnya adalah, Instant Article adalah bagian dari Facebook. Ketika mengeklik konten, pengguna tetap berada dalam Facebook, tidak pindah ke laman penerbit yang memiliki konten. Inilah dilema menggunakan Facebook bagi penerbit. Konten tersebar-luaskan sehingga iklan juga masuk melalui Facebook, namun sulit bagi penerbit untuk mendapatkan trafik organik ke laman mereka sendiri.
Bisa saja penerbit menghentikan kerja sama dengan Facebook atau dalam kasus di Australia, sebaliknya. Namun dilema berikutnya adalah, apakah media bisa meraup trafik yang signifikan hanya mengandalkan akses organik dan akses referral dari laman selain Facebook?
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.