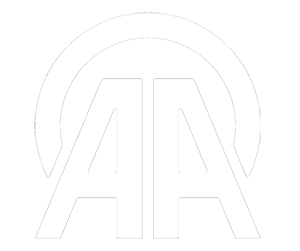Ilustrasi. Sebuah foto menunjukkan bangunan hancur dan kendaraan yang rusak setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 SR dan gelombang tsunami, di Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia pada 7 Oktober 2018. (Selman Tür - Anadolu Agency)
Ilustrasi. Sebuah foto menunjukkan bangunan hancur dan kendaraan yang rusak setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 SR dan gelombang tsunami, di Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia pada 7 Oktober 2018. (Selman Tür - Anadolu Agency)
Jakarta Raya
Hayati Nupus
JAKARTA
Manuskrip tua berbahasa arab itu menyebutkan kata smong atau seumong, yang berarti tsunami.
Ditemukan pada abad ke-19 di Zawiyah Tanoe Abee, Aceh Besar, manuskrip itu menceritakan adanya dua gempa besar yang terjadi pada Kamis Jumadil Akhir 1248 Hijriah atau 3 November 1832.
Manuskrip lainnya yang lebih tua, menurut pakar gempa Institut Teknologi Bandung Abdullah Sanny, ditemukan pada abad ke-18.
Berjudul Takbir Gempa, manuskrip yang kini tersimpan di Perpustakaan Ali Hasjmy, Banda Aceh, itu menyebutkan petunjuk gempa yang berlangsung sejak Subuh hingga tengah malam dalam 12 bulan.
“Jika gempa pada Bulan Rajab, pada waktu Subuh, alamatnya segala isi negeri bersusah hati dengan kekurangan makanan,” ujar Sanny, menuturkan isi manuskrip itu dalam Bahasa Indonesia, Rabu, di Jakarta.
“Jika pada waktu gempa itu, alamatnya air laut keras akan datang ke dalam negeri itu,” lanjut Sanny.
Aceh memiliki banyak manuskrip lama berisikan petunjuk gempa disertai datangnya gelombang raksasa dari laut, tutur Sanny. Mereka telah akrab dengan kata seumong atau ie beuna sejak abad ke-18.
Namun toh saat gempa melanda dasar laut Pulau Simeuleu disusul gelombang tsunami pada 2004, masyarakat belum juga siap.
Bencana itu memporak-porandakan Banda Aceh dan menewaskan lebih dari 200.000 jiwa.
“Karena tradisi dari manuskrip itu sudah lama dilupakan masyarakat,” kata Sanny.
Dari gempa, tsunami, hingga likuifaksi
Manuskrip-manuskrip warisan nenek moyang yang berisikan petunjuk gempa tak hanya dimiliki Aceh. Manuskrip serupa juga tersimpan di Sumatera Barat dan Palu.
Di Sumatera Barat, Filoloh Universitas Andalas, Zuriati, menemukan naskah Takwil Gempa yang isinya mirip dengan Takbir Gempa dari Aceh. Perpustakaan Nasional juga memiliki naskah Ramalan Gempa yang entah siapa pengarangnya. Manuskrip-manuskrip itu menunjukkan bahwa gempa bumi dan tsunami adalah masalah klasik, sudah berlangsung sejak lama di Indonesia.
Gempa dan tsunami Aceh misalnya, kata Sanny, berlangsung setiap 120 tahun sekali. Sedang gempa Palu akibat patahan sesar Palu-Koro berlangsung setiap 60 tahunan.
Masyarakat Palu juga memiliki manuskrip gempa dan tsunami seperti Aceh serta Sumatera Barat, ujar Sanny.
Seperti kedua wilayah itu, masyarakat Palu dan sekitarnya tak siap saat gempa berkekuatan M 7,4 disusul tsunami terjadi pada 28 September 2018.
Badan Nasional Penanganan Bencana mencatat gempa itu mengakibatkan lebih dari 2000 orang tewas dan 4000 lainnya tertimbun karena likuefaksi.
Likuifaksi, kata Sanny, merupakan hilangnya kekuatan lapisan tanah pasir akibat naiknya tekanan air dari dalam tanah saat gempa mengguncang dengan kuat dan berdurasi lama. Lapisan tanah pasir itu berubah menjadi cairan, kemudian menggerakkan tanah atau tersembur lewat rekahan.
Peringatan soal adanya likuifaksi telah dilakukan Badan Geologi pada 2012. Hasil kajian lembaga tersebut memetakan bahwa wilayah di Teluk Palu memiliki potensi tinggi untuk terjadinya likuifaksi. Peta itu juga menunjukkan Bandara Mutiara Sis Al Jufri yang tak jauh dari Petobo berada di zona potensi likuifaksi sangat tinggi. Pada gempa Palu 28 September lalu, perumanan di Petobo, Balaroa dan Jono Oge tenggelam akibat likuifaksi.
Indonesia memang wilayah rawan terjadi gempa bumi, ujar Sanny. Secara geografis negara ini berada di wilayah pertemuan empat lempeng besar dunia, yaitu Eurasia di sisi barat, Indo-Australia di sisi selatan, Pacific di sisi timur dan Asia di sisi utara.
“Seantero wilayah Indonesia itu rawan gempa, beberapa wilayah berpotensi tsunami,” jelas Sanny.
Indonesia rawan likuifaksi
Pakar likuifaksi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adrin Tohari mengatakan Indonesia tak hanya rawan gempa, melainkan juga likuifaksi.
Peristiwa likuifaksi di Palu bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Likuifaksi juga terjadi pada gempa-gempa besar sebelumnya, seperti gempa Aceh 2004, gempa gempa Bengkulu 2000 dan 2007, gempa Jogja 2006, gempa Padang 2009, bahkan gempa Lombok 2018.
Likuifaksi di wilayah-wilayah tersebut hanya berupa semburan pasir dan penurunan tanah, tidak sampai fenomena aliran seperti yang terjadi di Palu.
“Akan terjadi likuifaksi pada beberapa gempa besar yang terjadi di wilayah pesisir, tapi tidak serta merta sebesar kejadian di Palu,” kata Adrin.
Adrian menjelaskan bahwa manusia bisa memitigasi likuifaksi. Caranya dengan menghindari wilayah yang berpotensi terjadi likuifaksi dan berpindah ke wilayah lain yang lebih aman.
Agar terhindar, lanjut Adrin, rumah yang dibangun menggunakan struktur fleksibel dan fondasi dalam. Lebih aman lagi jika rumah-rumah itu berbahan kayu, seperti tradisi nenek moyang.
“Paling sederhana adalah menghindari membangun rumah vertikal, bikin saja rumah sederhana dengan struktur lentur,” kata Adrin.
Idealnya, menurut Sanny, setiap wilayah di Indonesia memiliki peta zonasi yang menjadi pedoman penataan ruang di wilayah tersebut. Setiap wilayah harus memiliki jalur evakuasi, sehingga ketika bencana terjadi mereka siap mengevakuasi diri. Dengan peta zonasi dan jalur evakuasi, dampak bencana dapat terminimalisir.
“Pemerintah sudah tau zoonasi itu, tapi diabaikan, mereka tidak pernah memperhatikan serius ancaman gempa bumi, tsunami dan likuifaksi,” keluh Sanny.
Sejauh ini, lanjut Sanny, provinsi yang sudah memiliki peta zonasi bencana baru Aceh dan Sumatera Barat.
Jika dibandingkan dengan Jepang, perhatian Indonesia soal bencana masih amat dangkal. Jepang mengalokasikan hingga Rp50 triliun per tahun untuk kebencanaan sedang Indonesia baru Rp5 triliun saja. Meski secara luasan wilayah Indonesia lebih besar dan lebih rentan terkena bencana.
Setiap ada kejadian bencana, menurut Sanny, Indonesia gencar menggaungkan soal pembentukan kultur baru yang siap menghadapi bencana. Namun itu sekadar wacana, gaung itu hilang seiring waktu dan baru terdengar lagi ketika bencana kembali terjadi dan menelan banyak korban jiwa.
Sekolah-sekolah di Jepang, kata Sanny, menggelar pelatihan kesiagaan gempa setiap semester. Mereka melakukan itu agar warga tak kaget dan siap mengevakuasi diri ketika bencana terjadi.
Indonesia perlu mencontoh Jepang bagaimana mensosialisasikan kebencanaan, ujar Sanny. Usulan untuk memasukkan kebencanaan ke kurikulum sekolah di Indonesia itu sudah dilakukan sejak gempa dan tsunami mengguncang Aceh, namun hingga kini belum ada perkembangan.
“Usulan itu tidak direspon, padahal cara itu lebih efektif untuk meminimalisir dampak bencana,” kata Sanny.
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.